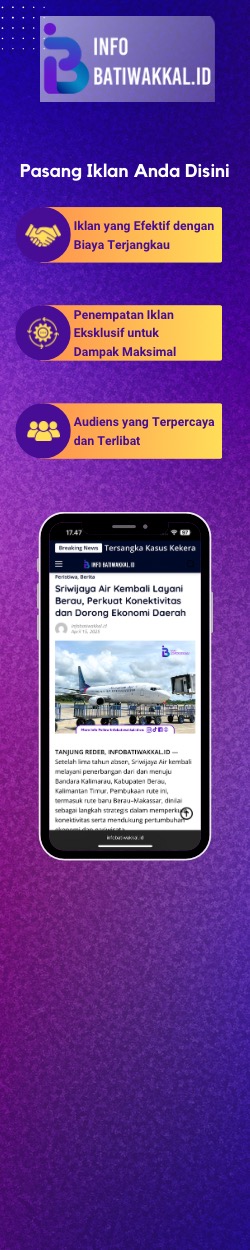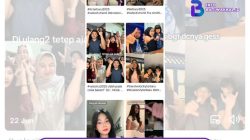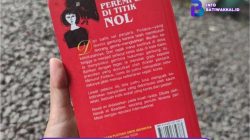ABSTRAK
Takbir keliling merupakan tradisi kolektif umat Islam Indonesia yang berlangsung pada malam menjelang Idulfitri dan Iduladha. Aktivitas ini bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga praktik budaya yang menampilkan kreativitas lokal melalui iringan bedug, obor, lampion, serta kendaraan hias. Tradisi ini menjadi ajang kebersamaan masyarakat dari berbagai generasi dan wilayah. Artikel ini menggunakan pendekatan post-strukturalisme dengan metode analisis wacana kritis Jacques Derrida untuk menelusuri bagaimana takbir keliling dimaknai, diregulasi, dan dikonstruksi dalam relasi kuasa antara masyarakat, negara, dan institusi keagamaan. Data diperoleh dari dokumentasi media, regulasi pemerintah, dan artikel akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa takbir keliling adalah arena produksi wacana yang tidak hanya mencerminkan nilai spiritual, tetapi juga pertarungan makna antara ekspresi keagamaan dan kontrol sosial. Tradisi ini membentuk identitas kolektif yang terus dinegosiasikan di Tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika politik lokal. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam ritual tersebut merupakan bentuk resistensi simbolik terhadap pembatasan ruang publik, serta artikulasi spiritualitas dalam bentuk performatif.
Kata kunci: takbir keliling, post-strukturalisme, Jacques Derrida, identitas kolektif, kekuasaan, ritual public
ABSTRACT
Takbir keliling is a collective tradition observed by Indonesian Muslims on the eve of Eid al Fitrand Eid al-Adha. Beyond its religious function, this practice involves cultural creativity such as traditional drums, torches, lanterns, and decorated vehicles. The event engages people from various generations and regions. This article employs a post-structuralist approach and Jacques Derrida’s critical discourse analysis to examine how takbir keliling is regulated, interpreted, and constructed through power relations involving communities, the state, and religious institutions. Data are drawn from media documentation, local government regulations, and academic literature.The analysis reveals that takbir keliling operates as a discursive field where spiritual values intersect with contestations of meaning, public space regulation, and cultural identity formation. The tradition embodies both spiritual expression and performative resistance to the state’s control over religious celebration.
Keywords: takbir keliling, post-structuralism, Michel Foucault, collective identity, power, public ritual
PENDAHULUAN
Takbir keliling adalah salah satu praktik khas umat Islam Indonesia yang dilakukan pada malam menjelang Idulfitri dan Iduladha. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara berkeliling di lingkungan kampung, desa, atau kota sambil mengumandangkan takbir secara berjamaah. Kegiatan ini seringkali diiringi dengan alat musik seperti bedug, rebana, atau bahkan sound system modern,serta dilengkapi dengan berbagai bentuk kreativitas visual berupa obor, lampion, miniatur masjid,dan kendaraan hias. Takbir keliling bukan hanya menjadi sarana merayakan hari besar keagamaan,tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan ekspresi budaya komunitas. Diberbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara,tradisi ini menjadi momen tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari berbagai usia.
Namun demikian, seiring berjalannya waktu, takbir keliling juga menghadapi tantangan dari aspek regulasi negara. Dalam beberapa konteks, kegiatan ini dibatasi atau bahkan dilarang dengan alasan menjaga ketertiban umum, menghindari kemacetan lalu lintas, dan potensi gangguan keamanan. Di sinilah terjadi pertarungan makna antara ekspresi keagamaan sebagai hak kolektif dan control negara atas ruang publik. Dalam konteks ini, ritual keagamaan seperti takbir keliling tidak hanya bisa dipahami sebagai manifestasi keimanan, tetapi juga sebagai praktik sosial-politik yang mengandung wacana kuasa, regulasi, dan negosiasi makna.
Dengan meminjam konsep-konsep dari Jacques Derrida, terutama mengenai différance, artikel ini berupaya mengurai bagaimana takbir keliling makna tersebut terus-menerus bergeser, saling menunda, dan bahkan bertentangan dengan dirinya sendiri. Pendekatan post-strukturalisme menawarkan cara pandang bahwa makna-makna sosial tidak bersifat tetap atau universal, melainkan dibentuk melalui praktik diskursif yang melibatkan aktor-aktor dominan dan subordinat. Oleh karena itu, takbir keliling dalam artikel ini akan dikaji sebagai praktik sosial yang plural dan tidak pernah final, serta sebagai representasi spiritualitas yang dikonstruksi dan dinegosiasikan melalui ruang public.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis yang berakar pada pemikiran Jacques Derrida. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana praktik takbir keliling tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga membongkar oposisi biner yang mungkin melekat tentang takbir keliling itu sendiri. Derrida berpendapat bahwa makna tidak pernah stabil, tunggal atau sepenuhnya hadir. Konsep différance ini menunjukan bahwa makna tidak pernah selesai atau final, tetapi selalu dalam proses pembentukan melalui jalinan perbedaan dan penundaan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer berupa dokumentasi visual dan narasi partisipatif dari masyarakat yang mengikuti takbir keliling, termasuk unggahan media sosial, video pawai, dan kutipan naratif dari peserta. Kedua, data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, berita daring dari media massa nasional, serta kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan takbir keliling. Data dikumpulkan secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus kajian.
Analisis dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dimodelkan oleh Derrida. Pertama, analisis pembongkaran oposisi biner dalam takbir keliling. Kedua, analisis konsep diferance dalam takbir keliling. Ketiga, jejak dan ketidakhadiran dalam representasi digital pemaknaan terhadap ritual ini dalam masyarakat kontemporer Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara tradisional, takbir keliling dianggap sebagai ritual yang murni sakral dan bersifat keagamaan. Namun, pendekatan dekonstruktif Derrida menunjukkan bahwa elemen-elemen yang dianggap profan tidak hanya menyertai, melainkan turut membentuk dan bahkan “ mengontaminasi ” makna sakral itu sendiri. Dalam praktiknya, banyak kelompok masyarakat yang berupaya memperindah perayaan ini dengan kreativitas yang bersifat performatif. Misalnya, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Idul fitri 2024, pemerintah daerah mendukung pawai takbir keliling yang menampilkan replika Ka ’ bah, masjid megah, dan kendaraan hias berlampu LED. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan menyaksikan acara ini, yang tidak hanya menjadi syiar Islam, tetapi juga hiburan komunal yang meriah (Radar Kudus, 2024).
Media sosial turut memperkuat dimensi ini. Komunitas Takbir Online Yogyakarta, misalnya, secara rutin mengadakan “lomba takbir digital” yang dikurasi berdasarkan jumlah views, likes, dan komentar di TikTok dan Instagram. Dalam konteks ini, modernitas tidak lagi menjadi tambahan
sekunder, melainkan kekuatan transformatif yang mengubah wajah dan makna dari tradisi itu sendiri. Makna spiritual bergeser menjadi estetika performatif — yang bisa dinilai, dibandingkan, dan dikompetisikan secara digital.
Konsep différance Derrida, yang menyatukan ide tentang perbedaan dan penundaan, menjelaskan bahwa makna suatu praktik sosial tidak pernah final. Takbir keliling tidak memiliki makna tunggal atau tetap. Penambahan elemen baru seperti dekorasi LED, sound system, atau konten media sosial, menunda pemahaman final tentang hakikat ritual itu. Variasi antara takbir keliling di Surabaya yang menampilkan kendaraan hias besar, dan di Sumedang yang lebih sederhana dan fokus pada kebersamaan warga desa, memperlihatkan bahwa keragaman inilah yang justru membentuk pemahaman menyeluruh tentang fenomena takbir keliling di Indonesia.
Fokus menarik dapat dilihat dari praktik takbir keliling di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Tradisiini setiap tahun digelar secara masif dan terorganisir, dengan dukungan penuh dari pemerintah kota. Pada malam Idulfitri 1444 H (2023), Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan lomba takbir keliling dengan rute yang melintasi pusat kota, dimulai dari Jam Gadang, ikon historis dan simbol budaya Minangkabau. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 50 kelompok peserta yang berasal dari berbagai masjid, surau, sekolah, dan organisasi masyarakat. Para peserta berjalan kaki membawa obor bambu, bedug tradisional, serta mengenakan pakaian adat Minang. Lantunan takbir dilakukan dengan pola irama khas Minang yang diiringi pantun religius dalam bahasa daerah (Pemerintah Kota Bukittinggi, 2023).
Penelitian oleh Lubis (2021) menyatakan bahwa surau-surau di Bukittinggi tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat produksi budaya Islam lokal. Anak-anak dan remaja dilatih untuk melantunkan takbir, memainkan bedug, dan menghafal pantun dakwah, yang kemudian ditampilkan saat takbir keliling. Takbir tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi sebagai ekspresi dari identitas kolektif yang menggabungkan nilai keislaman dan kearifan lokal Minangkabau.
Melalui perspektif différance, makna dari takbir keliling di Bukittinggi hadir dalam bentuk yang berbeda dari kota-kota lain. Pilihan untuk tetap berjalan kaki, menggunakan obor bambu, serta mempertahankan irama lokal, menandai perbedaan yang disengaja dari bentuk modern yang berorientasi pada kendaraan dan teknologi. Dalam konteks ini, yang tidak hadir — yakni kendaraan hias besar atau teknologi digital—justru menjadi bagian dari kehadiran makna. Keputusan tersebut menjadi bentuk negosiasi terhadap modernitas, sekaligus memperlihatkan bahwa makna spiritualitas dalam tradisi ini dibentuk oleh relasi antara yang hadir dan yang absen.
Selain itu, dokumentasi visual dari takbir keliling Bukittinggi yang diunggah di YouTube dan media lokal memperlihatkan narasi yang lebih terfokus pada kebersamaan dan ketertiban, alih-alih kemeriahan dan kompetisi visual. Judul-judul video seperti “Takbir Keliling Bukittinggi: Menggema di Tengah Adat dan Iman ” atau “ Surau Kami, Tradisi Kami ” menunjukkan bahwa praktik ini dikonstruksi sebagai pelestarian nilai dan spiritualitas, bukan sekadar hiburan publik. Dengan demikian, representasi digital dari takbir keliling di Bukittinggi mencerminkan nilai lokal yang berbeda dari dominasi citra metropolitan yang cenderung menonjolkan kemewahan visual.
Melalui lensa Derrida, dapat disimpulkan bahwa takbir keliling adalah arena différance — di mana makna terus berubah, diproduksi, ditunda, dan dinegosiasikan. Bukittinggi menjadi contoh konkret bahwa makna ritual kolektif keagamaan tidak bersifat universal, tetapi selalu dipengaruhi oleh konteks kultural, sosial, dan politik setempat. Takbir keliling tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga media artikulasi identitas, memori komunal, serta resistensi halus terhadap hegemoni makna tunggal yang dikonstruksi oleh modernitas dan pusat kekuasaan.
KESIMPULAN
Takbir keliling bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga arena produksi makna yang terus berubah sesuai konteks sosial dan budaya. Studi atas praktik di Bukittinggi menunjukkan bahwa elemen lokal seperti irama Minang, obor bambu, dan pantun religi membentuk makna spiritualitas yang berbeda dari kota-kota besa.r Analisis Derrida membuka pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang bagaimana ritual keagamaan kolektif berinteraksi dengan dinamika budaya, kekuasaan, dan teknologi dalam masyarakat kontemporer Indonesia, menunjukkan bahwa makna bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang terus-menerus diproduksi dalam jaringan perbedaan dan penundaan. Dengan demikian, takbir keliling dapat dipahami sebagai arena différance yang mencerminkan dinamika antara spiritualitas, budaya, kuasa, dan teknologi dalam masyarakat kontemporer.
DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, R. (2020). Transformasi Takbir Keliling sebagai Ekspresi Budaya Lokal di Malam Idul Fitri. Jurnal Komunikasi Islam, 12(2), 115–130.
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. Pantheon Books.
Hamzah, L. (2023). Takbir Keliling dan Representasi Budaya Islam Indonesia. Jurnal Sosial Budaya, 18(1), 45–60.
Lubis, A. (2021). Lomba Takbir Keliling sebagai Media Dakwah dan Hiburan Masyarakat. Jurnal Dakwah & Budaya, 7(2), 98–107.
Mubarok, S. (2022). Antara Ibadah dan Budaya: Perdebatan atas Takbir Keliling di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 20(1), 75–89.
Nugraha, A. (2023). Estetika dan Simbolisme dalam Takbir Keliling. Jurnal Seni & Budaya Islam, 11(1), 39–52.
Tempo.co. (2022). Pemerintah Larang Takbir Keliling, Ulama: Ini Tradisi Umat.
Wicaksono, D. (2021). Partisipasi Remaja dalam Takbir Keliling: Identitas dan Spiritualitas. Jurnal Remaja Islam, 3(2), 61–75.
Lubis, A. (2021). Lomba Takbir Keliling sebagai Media Dakwah dan Hiburan Masyarakat. Jurnal Dakwah & Budaya, 7(2), 98–107.
Pemerintah Kota Bukittinggi. (2023, April 20). Pemerintah Kota Bukittinggi Gelar Takbir Keliling Idul fitri 1444 H dengan Peserta dari 50 Kelompok Warga.
https://www.bukittinggikota.go.id/berita/takbir-keliling-2023
Radar Kudus. (2024, April 9). Meriah, Takbir Keliling di Pati Hadirkan Ka’bah dan Masjid Hiasan.
https://radarkudus.jawapos.com/pati-raya/1712627736964/meriah-takbir-keliling-di-pati-hadirkan–