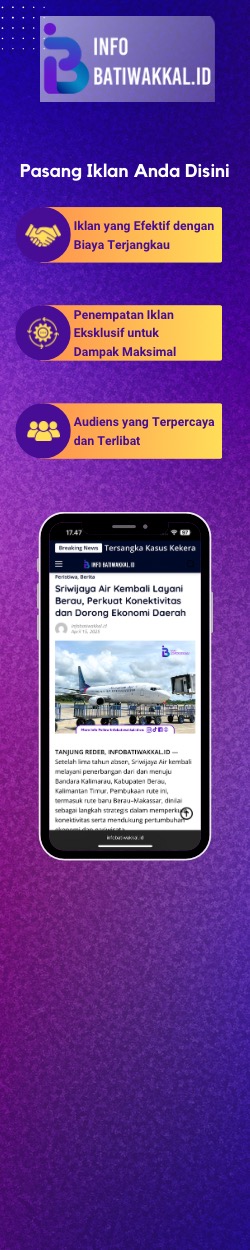Catatan dari Car Free Day HUT Bhayangkara ke-79 Polda Kaltim
Minggu pagi di Balikpapan bukan tentang parade. Bukan tentang pidato yang menggema atau derap pasukan yang membentuk barisan. Ia tentang jeda—tentang sebuah pagi yang sengaja dikosongkan dari lalu lintas, agar manusia bisa berjalan, bernapas, dan merasa hadir di tengah sesamanya.
Di Car Free Day Bhayangkara ke-79 yang berlangsung di Lapangan Merdeka, ada sesuatu yang lebih pelan dari biasanya. Tapi justru karena itu, terasa lebih dalam. Di balik tenda-tenda pelayanan seperti perpanjangan SIM, donor darah, klinik kesehatan, dan senam sehat, tersimpan sesuatu yang melampaui sekadar fungsi pelayanan publik.
Ia adalah jejak lembut dari negara—yang hadir bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kehadiran.
Di salah satu sudut, tampak Polwan Reni. Ia tidak sedang memberi perintah, tidak menjaga barikade. Ia berjoget kecil, berbaur dengan anak-anak yang mungkin belum tahu bahwa perempuan di hadapan mereka adalah aparat penegak hukum.
Kita diingatkan: negara tidak selalu hadir dalam rupa institusi yang kaku. Ia bisa hadir dalam tawa seorang anak yang disambut tos ringan dari seorang polisi perempuan. Dalam tarian kecil yang tidak lahir dari protokol, melainkan dari naluri kemanusiaan seorang ibu—karena Polwan Reni, sebelum menjadi aparat, adalah perempuan yang mengerti arti melindungi, bukan sekadar menertibkan.
Simone Weil, filsuf Prancis, pernah berkata bahwa “kekuatan sejati tidak pernah keras.” Ia tidak hadir dalam teriakan atau dominasi, tapi dalam pilihan untuk lembut. Ketika negara memilih menjadi pelayan, bukan penguasa.
Pagi itu, Car Free Day bukan hanya soal olahraga atau pelayanan. Ia soal relasi. Tentang bagaimana institusi sebesar Polri membuka dirinya untuk disentuh—dan menyentuh kembali—tanpa senjata, tanpa pagar kawat, tanpa jargon keamanan.
Dalam lanskap politik yang kerap memisahkan antara “kami” dan “mereka”, acara seperti ini menjadi ruang temu yang langka. Tidak semua hal harus dipertemukan melalui kotak suara atau layar debat. Kadang, cukup dengan gerak bersama. Dalam donor darah yang tak menanyakan latar belakang. Dalam pelayanan SIM yang tak membedakan siapa yang duduk di seberang meja.
Seperti yang pernah ditulis Hannah Arendt, politik yang sehat bukan soal kuasa, tapi soal kehadiran di ruang bersama.
Dan di ruang itu, pagi itu, negara hadir. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan berubah menjadi tempat orang tua menggandeng anaknya tertawa, polisi membantu lansia menyeberang, dan remaja belajar bahwa polisi bisa tersenyum, bahkan berjoget.
Ini bukan tentang perubahan sistem, tapi tentang perubahan wajah. Dari tegas menjadi hangat, dari birokratis menjadi manusiawi.
Kita sering membayangkan negara sebagai gedung tinggi dengan pagar besi, atau sebagai tangan yang mengatur. Tapi pagi itu, negara berjalan kaki bersama kita. Menunduk ketika berbicara pada anak kecil. Menyodorkan tangan pada mereka yang letih.
Car Free Day Bhayangkara bukanlah peristiwa besar. Tapi justru dalam ke-tidak-besarannya, ia penting. Karena di sana, kita tak hanya melihat wajah Polri. Kita melihat wajah rakyat—dan bagaimana keduanya bisa saling memandang tanpa curiga.
Barangkali inilah bentuk baru sacrum officium—tugas suci negara: bukan sekadar menjaga hukum, tapi menjaga harapan. Harapan bahwa kita masih bisa hidup berdampingan tanpa rasa takut, tanpa sekat.
Dan ketika acara itu usai, orang-orang pulang membawa oleh-oleh yang tak kasat mata: perasaan bahwa negara bukan sesuatu yang jauh. Bahwa Polri bukan hanya pelindung, tapi juga pelayan—dan kadang, teman bermain di jalan raya yang kosong.
Di jalan yang sunyi dari kendaraan itu, kita mendengar suara paling lirih dari demokrasi:
bahwa negara sejati adalah negara yang mau hadir, duduk, dan menunggu bersama warganya.
-@ESBE2025